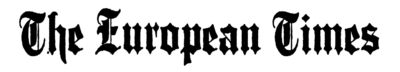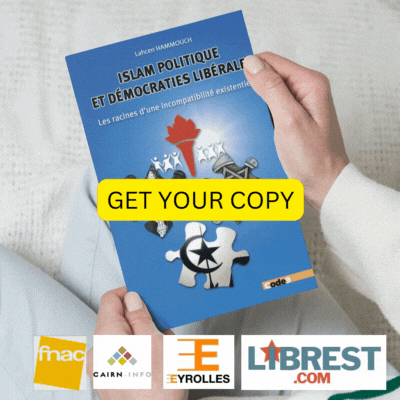Seperti dilansir melalui buletin dari LSM yang berbasis di Brussels Human Rights Without Frontiers, berakhirnya liburan musim panas di Prancis, yang dikenal sebagai “rentrée”, sering kali menimbulkan ketegangan sosial baru. Tahun ini mengikuti pola tersebut, karena ketenangan musim panas memberi jalan bagi perselisihan lain mengenai isu nasional yang berulang: bagaimana perempuan Muslim harus berpakaian.
Pada akhir Agustus, ketika Prancis masih libur, Gabriel Attal, menteri pendidikan berusia 34 tahun yang baru diangkat dan menjadi favorit Presiden Emmanuel Macron, mengumumkan bahwa “abaya tidak lagi bisa dikenakan di sekolah”, lapor Roger Cohen di itu
Perintahnya yang tiba-tiba, yang diterapkan pada sekolah menengah dan atas negeri, melarang jubah longgar yang dikenakan oleh beberapa siswa Muslim. Hal ini memicu perdebatan lain mengenai identitas Prancis.
Pemerintah percaya bahwa pendidikan harus menghilangkan perbedaan etnis atau agama sebagai bentuk komitmen bersama terhadap hak dan tanggung jawab warga negara Perancis. Seperti yang dikatakan Pak Attal, “Anda tidak seharusnya bisa membedakan atau mengidentifikasi agama siswa hanya dengan melihat mereka.”
Protes atas pelarangan abaya
Sejak pengumuman tersebut, organisasi Muslim yang mewakili sekitar 5 juta minoritas Muslim telah melakukan protes. Beberapa anak perempuan mengenakan kimono atau pakaian panjang lainnya ke sekolah untuk menunjukkan bahwa larangan tersebut terkesan sewenang-wenang. Perdebatan sengit terjadi mengenai apakah kejutan Tuan Attal pada bulan Agustus, tepat sebelum tahun ajaran baru, merupakan aksi politik atau perlunya pembelaan terhadap cita-cita sekuler Prancis.
“Attal ingin tampil tangguh demi keuntungan politik, tapi ini adalah keberanian murahan,” kata Nicolas Cadène, salah satu pendiri organisasi pemantau sekularisme di Prancis. “Keberanian nyata adalah mengatasi sekolah segregasi yang mengarah pada terpisahnya identitas etnis dan agama.”
Persoalan simbol agama di sekolah bukanlah hal baru. Perancis melarang penggunaan kata-kata yang “menonjol” pada tahun 2004, sehingga memberikan ruang untuk interpretasi.
Pertanyaannya adalah apakah undang-undang tersebut sama-sama menargetkan jilbab Muslim, salib Katolik, dan kippa Yahudi, atau hanya berfokus pada Islam. Abaya, yang mencerminkan identitas Muslim namun mungkin hanya pakaian sederhana, masih berada di area abu-abu hingga pernyataan Pak Attal.
Dalam praktiknya, “mewah” sering kali berarti Muslim. Kekhawatiran Perancis terhadap keretakan sekularisme, yang diperparah oleh serangan-serangan kelompok Islam yang menghancurkan, berpusat pada sikap umat Islam yang menjauhi “orang Prancis” karena identitas agama dan ekstremisme.
Niqab, kerudung, burkini, abaya dan bahkan jilbab dalam perjalanan sekolah mendapat perhatian yang tidak biasa di Prancis dibandingkan dengan Eropa dan khususnya Amerika Serikat, yang menekankan kebebasan beragama dibandingkan kebebasan beragama di Prancis.
Dalam beberapa tahun terakhir, sekularisme ketat, yang pada tahun 1905 dimaksudkan untuk menyingkirkan Gereja Katolik dari kehidupan publik, telah mengeras dari model yang mengizinkan kebebasan beragama yang diterima secara luas menjadi sebuah doktrin yang diperebutkan dan dianut oleh kelompok sayap kanan dan masyarakat luas sebagai pertahanan terhadap ancaman mulai dari ekstremisme Islam hingga ekstremisme Islam. Multikulturalisme Amerika.
“Hal ini seharusnya dilakukan pada tahun 2004, dan hal ini akan terjadi jika kita tidak memiliki pemimpin yang berani,” kata Marine Le Pen, pemimpin sayap kanan yang anti-imigrasi, mengenai langkah Attal. “Seperti yang diamati oleh Jenderal MacArthur, kekalahan dalam pertempuran dapat diringkas dalam dua kata: terlambat.”
Pertanyaannya adalah: terlambat untuk apa? Melarang abaya di sekolah sesuai tuntutan Pak Attal? Atau menghentikan penyebaran sekolah-sekolah yang kurang beruntung di pinggiran kota yang bermasalah dimana peluang bagi anak-anak imigran Muslim menderita dan risiko radikalisasi meningkat?
Di sinilah Perancis terpecah, dengan lebih dari 80 persen menyetujui larangan tersebut namun penting bagi masa depan negara tersebut.

Beberapa orang melihat sekularisme memungkinkan adanya kesempatan yang sama, sementara yang lain melihatnya sebagai hal yang sama kemunafikan menutupi prasangka, seperti yang diilustrasikan oleh daerah pinggiran kota tersebut.
Pemenggalan kepala guru Samuel Paty pada tahun 2020 oleh seorang ekstremis masih memicu kemarahan. Namun kerusuhan setelah penembakan oleh polisi terhadap remaja keturunan Aljazair dan Maroko menunjukkan kebencian atas risiko yang dirasakan umat Islam.
“Pemerintah Perancis menerapkan undang-undang tahun 1905 dan 2004 untuk 'melindungi nilai-nilai Republik' dari pakaian remaja, mengungkapkan kelemahannya dalam memungkinkan hidup berdampingan secara damai tanpa adanya perbedaan,” tulis sosiolog Agnès de Féo di Le Monde.
Éric Ciotti dari Partai Republik berhaluan kanan-tengah menjawab bahwa “communautarisme” atau memprioritaskan identitas agama/etnis di atas identitas nasional “mengancam Republik.” Pak Attal, katanya, merespons dengan tepat.
Partai Republik penting karena Macron tidak memiliki mayoritas di parlemen, sehingga kemungkinan besar mereka adalah sekutu legislatif.
Langkah Pak Attal memiliki tujuan politik yang jelas. Macron memerintah dari pusat namun condong ke kanan.
Attal menggantikan Pap Ndiaye, menteri pendidikan kulit hitam pertama, pada bulan Juli setelah serangan kelompok kanan memaksanya keluar, dengan rasisme terselubung di dalamnya.
Dia dituduh mengimpor “doktrin keberagaman” Amerika dan “mengurangi segalanya hanya sebatas warna kulit,” seperti yang dikatakan oleh kelompok sayap kanan Valeurs Actuelles.
Sebelum pemecatannya, Ndiaye menolak larangan abaya dan mengatakan bahwa kepala sekolah harus memutuskan kasus per kasus.
Sheik Sidibe, seorang asisten pengajar berkulit hitam berusia 21 tahun di luar sebuah sekolah menengah di Paris, mengatakan bahwa mantan kepala sekolahnya menganiaya siswa Muslim dengan pemeriksaan pakaian yang sewenang-wenang.
“Kita harus fokus pada masalah nyata, seperti rendahnya gaji guru,” kata Pak Sidibe, seorang Muslim. “Siswa marginal yang berada dalam situasi genting memerlukan bantuan, bukan pakaian pengamanan.”
Dampak politiknya masih belum jelas. Namun tindakan tersebut tampaknya lebih memecah belah dibandingkan mempersatukan meskipun ada tujuan sekularisme.
“Sekulerisme harus memungkinkan kebebasan dan kesetaraan apapun keyakinannya,” kata Cadène. “Ini tidak boleh menjadi senjata untuk membungkam masyarakat. Itu tidak akan membuatnya menarik.”