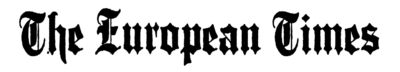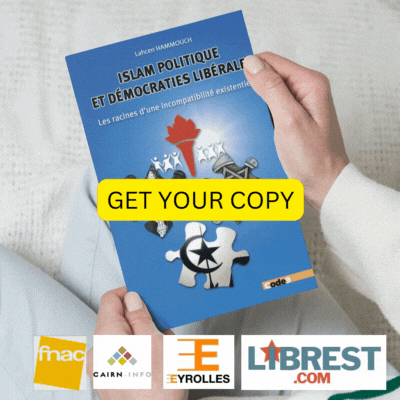Hubungan antara Fulani, korupsi dan neo-pastoralisme, yaitu pembelian ternak dalam jumlah besar oleh penduduk kota yang kaya untuk menyembunyikan uang haram.
Oleh Teodor Detchev
Dua bagian sebelumnya dari analisis ini, berjudul “Sahel – Konflik, Kudeta dan Bom Migrasi” dan “Fulani dan Jihadisme di Afrika Barat”, membahas kebangkitan aktivitas teroris di Afrika Barat. Afrika dan ketidakmampuan untuk mengakhiri perang gerilya yang dilancarkan kelompok Islam radikal melawan pasukan pemerintah di Mali, Burkina Faso, Niger, Chad dan Nigeria. Isu perang saudara yang sedang berlangsung di Republik Afrika Tengah juga dibahas.
Salah satu kesimpulan penting adalah bahwa semakin intensifnya konflik ini mempunyai risiko tinggi terjadinya “bom migrasi” yang akan menimbulkan tekanan migrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di sepanjang perbatasan selatan Uni Eropa. Keadaan penting juga adalah kemungkinan kebijakan luar negeri Rusia untuk memanipulasi intensitas konflik di negara-negara seperti Mali, Burkina Faso, Chad dan Republik Afrika Tengah. Karena berada dalam upaya untuk “melawan” potensi ledakan migrasi, Moskow dapat dengan mudah tergoda untuk menggunakan tekanan migrasi terhadap negara-negara UE yang pada umumnya sudah ditetapkan sebagai negara yang bermusuhan.
Dalam situasi berisiko ini, peran khusus dimainkan oleh suku Fulani – kelompok etnis semi-nomaden, peternak migran yang mendiami jalur dari Teluk Guinea hingga Laut Merah dan berjumlah 30 hingga 35 juta orang menurut berbagai data. . Sebagai kaum yang secara historis berperan sangat penting dalam masuknya Islam ke Afrika, khususnya Afrika Barat, suku Fulani menjadi godaan yang sangat besar bagi kaum radikal Islam, padahal mereka menganut mazhab sufi yang tidak diragukan lagi merupakan mazhab yang paling berpengaruh. toleran, sebagai dan yang paling mistis.
Sayangnya, seperti terlihat dari analisis di bawah ini, permasalahannya bukan hanya mengenai pertentangan agama. Konflik yang terjadi bukan hanya konflik etno-agama. Hal ini bersifat sosio-etno-religius, dan dalam beberapa tahun terakhir, dampak dari kekayaan yang dikumpulkan melalui korupsi, yang diubah menjadi kepemilikan ternak – yang disebut “neopastorisme” – mulai memberikan pengaruh yang lebih kuat. Fenomena ini merupakan ciri khas Nigeria dan menjadi pokok bahasan analisis bagian ketiga ini.
Suku Fulani di Nigeria
Menjadi negara terpadat di Afrika Barat dengan 190 juta penduduk, Nigeria, seperti banyak negara di kawasan ini, dicirikan oleh semacam dikotomi antara wilayah Selatan, yang sebagian besar dihuni oleh umat Kristen Yoruba, dan wilayah Utara, yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, dengan sebagian besar dari mereka adalah suku Fulani yang, seperti di tempat lain, adalah peternak hewan yang bermigrasi. Secara keseluruhan, negara ini berpenduduk 53% Muslim dan 47% Kristen.
“Sabuk tengah” Nigeria, yang melintasi negara itu dari timur ke barat, termasuk khususnya negara bagian Kaduna (utara Abuja), Dataran Tinggi Bunue (timur Abuja) dan Taraba (tenggara Abuja), merupakan titik pertemuan antara kedua dunia ini, tempat terjadinya insiden yang sering terjadi dalam siklus balas dendam yang tidak pernah berakhir antara para petani, biasanya beragama Kristen (yang menuduh para penggembala Fulani membiarkan ternak mereka merusak tanaman mereka) dan para penggembala Fulani yang nomaden (yang mengeluhkan pencurian ternak dan meningkatnya kemapanan). peternakan di wilayah yang secara tradisional dapat diakses oleh jalur migrasi hewan).
Konflik-konflik ini semakin meningkat dalam beberapa waktu terakhir, karena suku Fulani juga berupaya memperluas jalur migrasi dan penggembalaan ternak mereka ke selatan, dan padang rumput di utara menderita kekeringan yang semakin parah, sementara para petani di selatan, dalam kondisi kekeringan yang sangat tinggi. dinamika pertumbuhan penduduk, berupaya membangun pertanian lebih jauh ke utara.
Setelah tahun 2019, antagonisme ini berubah menjadi berbahaya ke arah identitas dan afiliasi keagamaan antara kedua komunitas tersebut, yang menjadi tidak dapat didamaikan dan diatur oleh sistem hukum yang berbeda, terutama sejak hukum Islam (Syariah) diperkenalkan kembali pada tahun 2000 di dua belas negara bagian di wilayah utara. (Hukum Islam berlaku sampai tahun 1960, setelah itu dihapuskan dengan kemerdekaan Nigeria). Dari sudut pandang umat Kristen, kaum Fulani ingin “mengislamkan” mereka – jika perlu dengan kekerasan.
Pandangan ini dipicu oleh fakta bahwa Boko Haram, yang menargetkan sebagian besar umat Kristen, berupaya menggunakan milisi bersenjata yang digunakan oleh Fulani untuk melawan lawan-lawan mereka, dan memang sejumlah pejuang ini telah bergabung dengan kelompok Islam tersebut. Umat Kristen percaya bahwa Fulani (bersama dengan Hausa, yang terkait dengan mereka) merupakan inti kekuatan Boko Haram. Persepsi ini berlebihan mengingat fakta bahwa sejumlah milisi Fulani masih bersifat otonom. Namun faktanya, pada tahun 2019 antagonisme tersebut semakin memburuk. [38]
Oleh karena itu, pada tanggal 23 Juni 2018, di sebuah desa yang sebagian besar dihuni oleh umat Kristen (dari kelompok etnis Lugere), sebuah serangan yang dikaitkan dengan suku Fulani menyebabkan banyak korban jiwa – 200 orang tewas.
Terpilihnya Muhammadu Buhari, seorang Fulani dan mantan pemimpin asosiasi budaya terbesar Fulani, Tabital Pulaakou International, sebagai Presiden Republik tidak membantu meredakan ketegangan. Presiden sering dituduh diam-diam mendukung orang tua Fulani, bukannya menginstruksikan pasukan keamanan untuk menindak aktivitas kriminal mereka.
Situasi suku Fulani di Nigeria juga menunjukkan beberapa tren baru dalam hubungan antara penggembala yang bermigrasi dan petani yang menetap. Pada tahun 2020, para peneliti telah menemukan adanya peningkatan nyata dalam jumlah konflik dan bentrokan antara penggembala dan petani.[5]
Neaopastoralim dan Fulani
Isu dan fakta seperti perubahan iklim, perluasan gurun pasir, konflik regional, pertumbuhan penduduk, perdagangan manusia dan terorisme telah dijadikan upaya untuk menjelaskan fenomena ini. Permasalahannya adalah tidak satu pun dari pertanyaan-pertanyaan tersebut yang dapat menjelaskan secara lengkap peningkatan tajam penggunaan senjata kecil dan senjata ringan oleh beberapa kelompok penggembala dan petani menetap. [5]
Olayinka Ajala secara khusus membahas pertanyaan ini, yang meneliti perubahan kepemilikan ternak selama bertahun-tahun, yang ia sebut “neopastoralisme”, sebagai penjelasan yang mungkin atas meningkatnya jumlah bentrokan bersenjata antara kelompok-kelompok ini.
Istilah neopastoralisme pertama kali digunakan oleh Matthew Luizza dari American Association for the Advancement of Science (Asosiasi Amerika untuk Kemajuan Ilmu Pengetahuan) untuk menggambarkan subversi terhadap bentuk tradisional peternakan hewan pastoral (migrasi) oleh elit perkotaan kaya yang berani berinvestasi dan terlibat dalam peternakan hewan tersebut untuk menyembunyikan barang curian. atau harta haram. (Luizza, Matthew, para penggembala Afrika telah terjerumus ke dalam kemiskinan dan kejahatan, 9 November 2017, The Economist). [8]
Sementara itu, Olayinka Ajala mendefinisikan neo-pastoralisme sebagai bentuk baru kepemilikan ternak yang ditandai dengan kepemilikan sejumlah besar ternak oleh orang-orang yang bukan penggembala. Oleh karena itu, kawanan domba ini dilayani oleh para gembala sewaan. Mengatasi kawanan ternak ini sering kali memerlukan penggunaan senjata dan amunisi canggih, yang berasal dari kebutuhan untuk menyembunyikan kekayaan curian, hasil perdagangan manusia, atau pendapatan yang diperoleh melalui aktivitas teroris, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi investor. Penting untuk dicatat bahwa definisi non-pastoralisme menurut Ajala Olayinka tidak mencakup investasi pada ternak yang dibiayai dengan cara yang sah. Memang ada, namun jumlahnya sedikit sehingga tidak masuk dalam cakupan kepentingan penelitian penulis.[5]
Peternakan ternak migran yang merumput secara tradisional berskala kecil, ternaknya dimiliki oleh keluarga dan biasanya diasosiasikan dengan kelompok etnis tertentu. Aktivitas peternakan ini dikaitkan dengan berbagai risiko, serta upaya besar yang diperlukan untuk memindahkan ternak sejauh ratusan kilometer untuk mencari padang rumput. Semua ini membuat profesi ini tidak begitu populer dan dilakukan oleh beberapa kelompok etnis, di antaranya adalah suku Fulani yang menonjol, yang telah menjadi pekerjaan utama selama beberapa dekade. Selain menjadi salah satu kelompok etnis terbesar di Sahel dan Sub-Sahara Afrika, beberapa sumber menyebutkan suku Fulani di Nigeria berjumlah sekitar 17 juta orang. Selain itu, ternak sering kali dipandang sebagai sumber keamanan dan indikator kekayaan, dan oleh karena itu para penggembala tradisional melakukan penjualan ternak dalam skala yang sangat terbatas.
Pastoralisme Tradisional
Neopastoralisme berbeda dengan pastoralisme tradisional dalam hal bentuk kepemilikan ternak, rata-rata jumlah ternak, dan penggunaan senjata. Meskipun jumlah rata-rata kawanan ternak secara tradisional bervariasi antara 16 dan 69 ekor sapi, ukuran kawanan non-pastoral biasanya berkisar antara 50 dan 1,000 ekor sapi, dan keterlibatan di sekitar mereka sering kali melibatkan penggunaan senjata api oleh para penggembala sewaan. [8], [5]
Meskipun sebelumnya di Sahel merupakan hal yang lumrah jika kawanan ternak dalam jumlah besar ditemani oleh tentara bersenjata, kini kepemilikan ternak semakin dipandang sebagai cara untuk menyembunyikan kekayaan haram dari para politisi korup. Selain itu, meskipun para penggembala tradisional berusaha menjalin hubungan baik dengan para petani untuk mempertahankan interaksi simbiosis dengan mereka, para penggembala bayaran tidak memiliki insentif untuk berinvestasi dalam hubungan sosial mereka dengan para petani karena mereka memiliki senjata yang dapat digunakan untuk mengintimidasi para petani. [5], [8]
Khususnya di Nigeria, ada tiga alasan utama munculnya neo-pastoralisme. Pertama, kepemilikan ternak tampaknya merupakan investasi yang menggiurkan karena harga yang terus meningkat. Seekor sapi dewasa secara seksual di Nigeria berharga US$1,000 dan hal ini membuat peternakan sapi menjadi bidang yang menarik bagi calon investor. [5]
Kedua, terdapat hubungan langsung antara neo-pastoralisme dan praktik korupsi di Nigeria. Sejumlah peneliti berpendapat bahwa korupsi adalah akar dari sebagian besar pemberontakan dan pemberontakan bersenjata di negara ini. Pada tahun 2014, salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk memberantas korupsi, khususnya pencucian uang, diperkenalkan. Ini adalah entri Nomor Verifikasi Bank (BVN). Tujuan BVN adalah untuk memantau transaksi bank dan mengurangi atau menghilangkan pencucian uang. [5]
Nomor Verifikasi Bank (BVN) menggunakan teknologi biometrik untuk mendaftarkan setiap pelanggan ke semua bank Nigeria. Setiap nasabah kemudian diberikan kode identifikasi unik yang menghubungkan semua rekening mereka sehingga mereka dapat dengan mudah memantau transaksi antar beberapa bank. Tujuannya adalah untuk memastikan transaksi mencurigakan mudah diidentifikasi karena sistem menangkap gambar dan sidik jari seluruh nasabah bank, sehingga menyulitkan dana ilegal untuk disetorkan ke rekening berbeda oleh orang yang sama. Data dari wawancara mendalam mengungkapkan bahwa BVN mempersulit pejabat politik untuk menyembunyikan kekayaan haram, dan sejumlah rekening yang terkait dengan politisi dan kroni-kroninya, yang diduga menerima dana curian, dibekukan setelah diperkenalkan.
Bank Sentral Nigeria melaporkan bahwa “beberapa miliar naira (mata uang Nigeria) dan jutaan mata uang asing lainnya terperangkap dalam rekening di sejumlah bank, dan pemilik rekening tersebut tiba-tiba berhenti berbisnis dengan bank tersebut. Akhirnya, lebih dari 30 juta akun “pasif” dan tidak terpakai telah diidentifikasi sejak diperkenalkannya BVN di Nigeria pada tahun 2020. [5]
Wawancara mendalam yang dilakukan oleh penulis mengungkapkan bahwa banyak orang yang telah menyimpan sejumlah besar uang di bank Nigeria sebelum diperkenalkannya Nomor Verifikasi Bank (BVN) bergegas untuk menariknya. Beberapa minggu sebelum batas waktu bagi siapa pun yang menggunakan layanan perbankan untuk mendapatkan BVN, pejabat bank di Nigeria menyaksikan aliran uang tunai yang dicairkan secara massal dari berbagai cabang di negara tersebut. Tentu saja, kita tidak dapat mengatakan bahwa semua uang tersebut dicuri atau merupakan akibat dari penyalahgunaan kekuasaan, namun merupakan sebuah fakta bahwa banyak politisi di Nigeria beralih ke uang tunai karena mereka tidak ingin diawasi oleh bank. [5]
Saat ini, aliran dana haram telah dialihkan ke sektor pertanian, dengan jumlah pembelian hewan ternak yang sangat besar. Pakar keamanan finansial sepakat bahwa sejak diperkenalkannya BVN, terjadi peningkatan tajam dalam jumlah orang yang menggunakan kekayaan haram untuk membeli ternak. Mengingat fakta bahwa pada tahun 2019 seekor sapi dewasa berharga 200,000 – 400,000 Naira (600 hingga 110 USD) dan tidak ada mekanisme untuk menetapkan kepemilikan sapi, maka mudah bagi para koruptor untuk membeli ratusan sapi seharga jutaan Naira. Hal ini menyebabkan kenaikan harga ternak, dimana sejumlah besar ternak kini dimiliki oleh masyarakat yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan peternakan sapi sebagai pekerjaan dan kehidupan sehari-hari, bahkan beberapa pemiliknya berasal dari daerah yang jauh dari tempat penggembalaan. daerah. [5]
Seperti dibahas di atas, hal ini menciptakan risiko keamanan besar lainnya di wilayah rangeland, karena para penggembala tentara bayaran seringkali bersenjata lengkap.
Ketiga, kaum neopastoralis menjelaskan pola baru hubungan neopatrimonial antara pemilik dan penggembala dengan meningkatnya tingkat kemiskinan di antara mereka yang bergerak di industri. Meskipun harga ternak meningkat selama beberapa dekade terakhir dan perluasan peternakan di pasar ekspor, kemiskinan di kalangan peternak migran tidak berkurang. Sebaliknya, menurut data peneliti Nigeria, dalam 30-40 tahun terakhir, jumlah penggembala miskin meningkat tajam. (Catley, Andy dan Alula Iyasu, Pindah atau pindah? Analisis Cepat Penghidupan dan Konflik di Mieso-Mulu Woreda, Shinile Zone, Wilayah Somalia, Ethiopia, April 2010, Feinstein International Center).
Bagi mereka yang berada di lapisan terbawah dalam komunitas pastoral, bekerja untuk pemilik ternak dalam jumlah besar menjadi satu-satunya pilihan untuk bertahan hidup. Dalam lingkungan neo-pastoral, meningkatnya kemiskinan di kalangan komunitas penggembala, yang menyebabkan para penggembala tradisional gulung tikar, menjadikan mereka mangsa empuk bagi “pemilik yang tidak hadir” sebagai tenaga kerja murah. Di beberapa tempat di mana anggota kabinet politik memiliki ternak, anggota komunitas penggembala atau penggembala dari kelompok etnis tertentu yang telah terlibat dalam kegiatan ini selama berabad-abad, sering kali menerima imbalan dalam bentuk dana yang disajikan sebagai “dukungan untuk masyarakat lokal. komunitas”. Dengan cara ini, kekayaan yang diperoleh secara ilegal menjadi sah. Hubungan patron-klien ini terutama terjadi di Nigeria bagian utara (rumah bagi sebagian besar penggembala migran tradisional, termasuk suku Fulani), yang dianggap dibantu oleh pihak berwenang dengan cara ini. [5]
Dalam hal ini, Ajala Olayinka menggunakan kasus Nigeria sebagai studi kasus untuk mengeksplorasi secara mendalam pola-pola konflik baru ini mengingat negara tersebut memiliki konsentrasi ternak terbesar di kawasan Afrika Barat dan Afrika Sub – Sahara – sekitar 20 juta ekor. ternak. Oleh karena itu, jumlah penggembala juga sangat tinggi dibandingkan daerah lain, dan skala konflik di negara ini sangat serius. [5]
Harus ditekankan di sini bahwa hal ini juga berkaitan dengan pergeseran geografis dari pusat gravitasi dan migrasi pastoral ke pertanian dan konflik-konflik terkait dari negara-negara Tanduk Afrika, dimana di masa lalu hal ini paling dianjurkan ke Afrika Barat dan Afrika Barat. khususnya – ke Nigeria. Baik jumlah ternak yang dipelihara maupun skala konflik secara bertahap berpindah dari negara-negara Tanduk Afrika ke barat, dan saat ini fokus permasalahan ini ada di Nigeria, Ghana, Mali, Niger, Mauritania, Pantai Gading. 'Gading dan Senegal. Kebenaran pernyataan ini sepenuhnya dikonfirmasi oleh data Proyek Data Lokasi dan Peristiwa Konflik Bersenjata (ACLED). Sekali lagi menurut sumber yang sama, bentrokan dan kematian yang terjadi di Nigeria lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain yang mengalami masalah serupa.
Temuan Olayinka didasarkan pada penelitian lapangan dan penggunaan metode kualitatif seperti wawancara mendalam yang dilakukan di Nigeria antara tahun 2013 dan 2019. [5]
Secara garis besar, penelitian ini menjelaskan bahwa pastoralisme tradisional dan pastoralisme migrasi secara bertahap digantikan oleh neopastoralisme, suatu bentuk pastoralisme yang ditandai dengan jumlah ternak yang jauh lebih besar dan peningkatan penggunaan senjata dan amunisi untuk melindungi mereka. [5]
Salah satu konsekuensi utama dari non-pastoralisme di Nigeria adalah meningkatnya jumlah insiden dan akibatnya adalah dinamika pencurian dan penculikan ternak di daerah pedesaan. Hal ini sendiri bukanlah fenomena baru dan telah diamati sejak lama. Menurut peneliti seperti Aziz Olanian dan Yahaya Aliyu, selama beberapa dekade, penggembalaan ternak “dilokalisasi, musiman, dan dilakukan dengan senjata yang lebih tradisional dengan tingkat kekerasan yang rendah.” (Olaniyan, Azeez dan Yahaya Aliyu, Sapi, Bandit dan Konflik Kekerasan: Memahami Gemerisik Sapi di Nigeria Utara, Dalam: Africa Spectrum, Vol. 51, Edisi 3, 2016, hlm. 93 – 105).
Menurut mereka, selama periode yang panjang (tapi sepertinya sudah lama berlalu) ini, gemerisik ternak dan kesejahteraan para penggembala yang bermigrasi berjalan beriringan, dan gemerisik ternak bahkan dipandang sebagai “alat untuk redistribusi sumber daya dan perluasan wilayah oleh komunitas penggembala.” ”. .
Untuk mencegah terjadinya anarki, para pemimpin komunitas pastoral telah membuat peraturan untuk penggembalaan ternak (!) yang tidak mengizinkan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Pembunuhan selama pencurian ternak juga dilarang.
Aturan-aturan ini diterapkan tidak hanya di Afrika Barat, seperti yang dilaporkan oleh Olanian dan Aliyu, namun juga di Afrika Timur, di selatan Tanduk Afrika, misalnya di Kenya, tempat Ryan Trichet melaporkan pendekatan serupa. (Triche, Ryan, Konflik pastoral di Kenya: mengubah kekerasan mimesis menjadi berkat mimesis antara komunitas Turkana dan Pokot, jurnal Afrika tentang Resolusi Konflik, Vol. 14, No. 2, hal. 81-101).
Pada saat itu, peternakan hewan migrasi dan penggembalaan dilakukan oleh kelompok etnis tertentu (yang paling menonjol adalah suku Fulani) yang hidup dalam komunitas yang sangat terhubung dan terjalin, berbagi budaya, nilai-nilai dan agama yang sama, sehingga membantu menyelesaikan perselisihan dan konflik yang timbul. . penyelesaian tanpa meningkat menjadi bentuk kekerasan yang ekstrim. [5]
Salah satu perbedaan utama antara pencurian ternak di masa lalu, beberapa dekade yang lalu, dan saat ini adalah logika di balik tindakan mencuri. Di masa lalu, motif pencurian ternak adalah untuk memulihkan sejumlah kerugian dalam ternak keluarga, atau untuk membayar mahar di pesta pernikahan, atau untuk menyamakan perbedaan kekayaan di antara masing-masing keluarga, namun secara kiasan “hal tersebut tidak berorientasi pada pasar. dan motif utama pencurian tersebut bukanlah untuk mengejar tujuan ekonomi apapun”. Dan di sini situasi ini terjadi di Afrika Barat dan Timur. (Fleisher, Michael L., “Perang baik untuk Pencuri!”: Simbiosis Kejahatan dan Peperangan di antara Kuria Tanzania, Afrika: Jurnal Institut Afrika Internasional, Vol. 72, No. 1, 2002, hal. 131 -149).
Hal sebaliknya terjadi pada dekade terakhir, dimana kita menyaksikan pencurian hewan ternak yang sebagian besar dimotivasi oleh pertimbangan kesejahteraan ekonomi, yang secara kiasan “berorientasi pasar”. Sebagian besar dicuri demi keuntungan, bukan karena rasa iri atau kebutuhan yang ekstrim. Sampai batas tertentu, penyebaran pendekatan dan praktik ini juga dapat disebabkan oleh keadaan seperti meningkatnya biaya peternakan, meningkatnya permintaan daging karena pertumbuhan populasi, dan kemudahan memperoleh senjata. [5]
Penelitian Aziz Olanian dan Yahaya Aliyu membuktikan dan membuktikan adanya hubungan langsung antara neo-pastoralisme dan peningkatan volume pencurian ternak di Nigeria. Peristiwa yang terjadi di beberapa negara Afrika telah meningkatkan proliferasi senjata (proliferasi) di wilayah tersebut, dengan tentara bayaran yang baru menjadi penggembala dibekali dengan senjata “perlindungan kawanan”, yang juga digunakan dalam pencurian ternak.
Proliferasi senjata
Fenomena ini mengambil dimensi baru setelah tahun 2011, ketika puluhan ribu senjata kecil menyebar dari Libya ke sejumlah negara di Sahel Sahara, serta ke Afrika Sub-Sahara secara keseluruhan. Pengamatan ini telah sepenuhnya dikonfirmasi oleh “panel ahli” yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB, yang antara lain juga mengkaji konflik di Libya. Para ahli mencatat bahwa pemberontakan di Libya dan pertempuran yang terjadi setelahnya telah menyebabkan proliferasi senjata yang belum pernah terjadi sebelumnya, tidak hanya di negara-negara tetangga Libya, tetapi juga di seluruh benua.
Menurut para ahli Dewan Keamanan PBB yang telah mengumpulkan data rinci dari 14 negara Afrika, Nigeria adalah salah satu negara yang paling terkena dampak dari maraknya proliferasi senjata yang berasal dari Libya. Senjata diselundupkan ke Nigeria dan negara-negara lain melalui Republik Afrika Tengah (CAR), dan pengiriman ini memicu konflik, ketidakamanan, dan terorisme di beberapa negara Afrika. (Strazzari, Francesco, Libyan Arms and Regional Instability, The International Spectator. Italian Journal of International Affairs, Vol. 49, Issue 3, 2014, pp. 54-68).
Meskipun konflik Libya telah lama dan terus menjadi sumber utama proliferasi senjata di Afrika, terdapat konflik aktif lainnya yang juga memicu aliran senjata ke berbagai kelompok, termasuk kelompok neo-pastoralis di Nigeria dan Sahel. Daftar konflik tersebut antara lain Sudan Selatan, Somalia, Mali, Republik Afrika Tengah, Burundi dan Republik Demokratik Kongo. Diperkirakan pada bulan Maret 2017 terdapat lebih dari 100 juta senjata kecil dan ringan (SALW) di zona krisis di seluruh dunia, dan sebagian besar digunakan di Afrika.
Industri perdagangan senjata ilegal tumbuh subur di Afrika, dimana perbatasan yang “keropos” merupakan hal yang umum di sebagian besar negara, dan senjata bergerak bebas melintasi negara-negara tersebut. Meskipun sebagian besar senjata selundupan berakhir di tangan kelompok pemberontak dan teroris, para penggembala yang bermigrasi juga semakin banyak menggunakan senjata kecil dan ringan (SALW). Misalnya, para penggembala di Sudan dan Sudan Selatan telah secara terbuka memamerkan senjata kecil dan ringan (SALW) mereka selama lebih dari 10 tahun. Meskipun banyak penggembala tradisional masih terlihat di Nigeria menggembalakan ternak dengan tongkat di tangan, sejumlah penggembala migran terlihat membawa senjata kecil dan ringan (SALW) dan beberapa dituduh terlibat dalam penggembalaan ternak. Selama dekade terakhir, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah pencurian ternak, yang mengakibatkan kematian tidak hanya pada penggembala tradisional, namun juga petani, petugas keamanan, dan warga lainnya. (Adeniyi, Adesoji, The Human Cost of Uncontroll Arms in Africa, Penelitian lintas nasional di tujuh negara Afrika, Maret 2017, Oxfam Research Reports).
Selain penggembala sewaan yang menggunakan senjata yang mereka miliki untuk melakukan penggembalaan ternak, ada juga bandit profesional yang terutama terlibat dalam penggembalaan ternak bersenjata di beberapa wilayah Nigeria. Neo-penggembala sering mengklaim bahwa mereka membutuhkan perlindungan dari para bandit ketika menjelaskan tentang mempersenjatai para penggembala. Beberapa peternak yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka membawa senjata untuk melindungi diri dari bandit yang menyerang mereka dengan tujuan mencuri ternak mereka. (Kuna, Mohammad J. dan Jibrin Ibrahim (eds.), Bandit dan konflik pedesaan di Nigeria utara, Pusat Demokrasi dan Pembangunan, Abuja, 2015, ISBN: 9789789521685, 9789521685).
Sekretaris Nasional Asosiasi Peternak Ternak Miyetti Allah Nigeria (salah satu asosiasi peternak terbesar di negara ini) menyatakan: “Jika Anda melihat seorang pria Fulani membawa AK-47, itu karena gemerisik ternak sudah begitu merajalela sehingga dia bertanya-tanya apakah ada keamanan di negara ini”. (Pemimpin nasional Fulani: Mengapa para penggembala kita membawa AK47., 2 Mei 2016, 1, The News).
Kerumitan ini disebabkan oleh fakta bahwa senjata yang diperoleh untuk mencegah penggembalaan ternak juga digunakan secara bebas ketika terjadi konflik antara penggembala dan petani. Bentrokan kepentingan seputar ternak yang bermigrasi ini telah menyebabkan perlombaan senjata dan menciptakan lingkungan seperti medan perang karena semakin banyak penggembala tradisional yang juga terpaksa membawa senjata untuk mempertahankan diri bersama ternak mereka. Dinamika yang berubah ini mengarah pada gelombang kekerasan baru dan sering kali secara kolektif disebut sebagai “konflik pastoral”. [5]
Meningkatnya jumlah dan intensitas bentrokan dan kekerasan parah antara petani dan penggembala juga diyakini sebagai konsekuensi dari tumbuhnya neo-pastoralisme. Tidak termasuk kematian akibat serangan teroris, bentrokan antara petani dan penggembala merupakan penyebab kematian terbesar terkait konflik pada tahun 2017. (Kazeem, Yomi, Nigeria kini memiliki ancaman keamanan dalam negeri yang lebih besar dibandingkan Boko Haram, 19 Januari 2017, Quarz).
Meskipun bentrokan dan perseteruan antara petani dan penggembala migran sudah berlangsung berabad-abad, yakni sebelum era kolonial, dinamika konflik-konflik ini telah berubah secara dramatis. (Ajala, Olayinka, Mengapa bentrokan meningkat antara petani dan penggembala di Sahel, 2 Mei 2018, 2.56 CEST, The Conversation).
Pada masa pra-kolonial, penggembala dan petani sering hidup berdampingan dalam simbiosis karena bentuk pertanian dan jumlah ternak. Ternak merumput di tunggul yang ditinggalkan petani setelah panen, paling sering terjadi pada musim kemarau ketika para penggembala yang bermigrasi memindahkan ternaknya lebih jauh ke selatan untuk merumput di sana. Sebagai imbalan atas jaminan penggembalaan dan hak akses yang diberikan oleh para petani, kotoran sapi digunakan oleh para petani sebagai pupuk alami untuk lahan pertanian mereka. Saat ini adalah masa dimana pertanian skala kecil dan kepemilikan hewan ternak dilakukan oleh keluarga, dan baik petani maupun peternak mendapatkan manfaat dari pemahaman mereka. Dari waktu ke waktu, ketika penggembalaan ternak menghancurkan hasil pertanian dan timbul konflik, mekanisme penyelesaian konflik lokal diterapkan dan perbedaan antara petani dan penggembala diselesaikan, biasanya tanpa menggunakan kekerasan. [5] Selain itu, para petani dan penggembala yang bermigrasi sering kali membuat skema pertukaran gandum dengan susu yang memperkuat hubungan mereka.
Namun model pertanian ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Isu-isu seperti perubahan pola produksi pertanian, ledakan penduduk, berkembangnya hubungan pasar dan kapitalis, perubahan iklim, menyusutnya luas Danau Chad, persaingan atas tanah dan air, hak untuk menggunakan jalur pastoral migrasi, kekeringan dan perluasan gurun (desertifikasi), peningkatan diferensiasi etnis dan manipulasi politik disebut-sebut sebagai alasan perubahan dinamika hubungan antara petani dan peternak yang bermigrasi. Davidheiser dan Luna mengidentifikasi kombinasi kolonisasi dan pengenalan hubungan pasar-kapitalis di Afrika sebagai salah satu penyebab utama konflik antara penggembala dan petani di benua tersebut. (Davidheiser, Mark dan Aniuska Luna, Dari Komplementaritas ke Konflik: Analisis Sejarah Hubungan Farmet – Fulbe di Afrika Barat, Jurnal Afrika tentang Resolusi Konflik, Vol. 8, No. 1, 2008, hlm. 77 – 104).
Mereka berpendapat bahwa perubahan undang-undang kepemilikan tanah yang terjadi pada masa kolonial, dikombinasikan dengan perubahan teknik pertanian setelah penerapan metode pertanian modern seperti pertanian beririgasi dan diperkenalkannya “skema untuk membiasakan para penggembala yang bermigrasi untuk hidup menetap”, melanggar undang-undang tersebut. hubungan simbiosis sebelumnya antara petani dan penggembala, meningkatkan kemungkinan konflik antara kedua kelompok sosial ini.
Analisis yang ditawarkan Davidheiser dan Luna berpendapat bahwa integrasi antara hubungan pasar dan cara produksi modern telah menyebabkan pergeseran dari “hubungan berbasis pertukaran” antara petani dan penggembala yang bermigrasi ke “marketisasi dan komodifikasi” dan komoditisasi produksi), yang meningkatkan tekanan permintaan sumber daya alam antara kedua negara dan mengganggu stabilitas hubungan yang sebelumnya saling simbiosis.
Perubahan iklim juga disebut-sebut sebagai salah satu penyebab utama konflik antara petani dan penggembala di Afrika Barat. Dalam studi kuantitatif yang dilakukan di Negara Bagian Kano, Nigeria pada tahun 2010, Haliru mengidentifikasi perambahan gurun ke lahan pertanian sebagai sumber utama perebutan sumber daya yang menyebabkan konflik antara penggembala dan petani di Nigeria utara. (Halliru, Salisu Lawal, Implikasi Keamanan Perubahan Iklim Antara Petani dan Peternak Sapi di Nigeria Utara: Studi Kasus Tiga Komunitas di Pemerintah Daerah Kura Negara Bagian Kano. Dalam: Leal Filho, W. (eds) Buku Panduan Adaptasi Perubahan Iklim, Springer, Berlin, Heidelberg, 2015).
Perubahan tingkat curah hujan telah mengubah pola migrasi para penggembala, dimana para penggembala bergerak lebih jauh ke selatan menuju wilayah di mana ternak mereka biasanya tidak merumput pada dekade-dekade sebelumnya. Contohnya adalah dampak kekeringan berkepanjangan di wilayah gurun Sudan-Sahel, yang semakin parah sejak tahun 1970. (Fasona, Mayowa J. dan AS Omojola, Climate Change, Human Security and Communal Clashes in Nigeria, 22 – 23 Juni 2005, Prosiding Lokakarya Internasional tentang Keamanan Manusia dan Perubahan Iklim, Hotel Holmen Fjord, Asker dekat Oslo, Perubahan Lingkungan Global dan Keamanan Manusia (GECHS), Oslo).
Pola migrasi baru ini meningkatkan tekanan terhadap lahan dan sumber daya tanah, sehingga menyebabkan konflik antara petani dan penggembala. Dalam kasus lain, peningkatan populasi komunitas petani dan penggembala juga berkontribusi terhadap tekanan terhadap lingkungan.
Meskipun isu-isu yang tercantum di sini berkontribusi terhadap semakin dalamnya konflik, terdapat perbedaan nyata dalam beberapa tahun terakhir dalam hal intensitas, jenis senjata yang digunakan, metode penyerangan dan jumlah kematian yang tercatat dalam konflik tersebut. Jumlah serangan juga meningkat secara signifikan selama dekade terakhir, terutama di Nigeria.
Data dari database ACLED menunjukkan bahwa konflik tersebut menjadi lebih parah sejak tahun 2011, menyoroti kemungkinan kaitannya dengan perang saudara di Libya dan proliferasi senjata yang diakibatkannya. Meskipun jumlah serangan dan jumlah korban telah meningkat di sebagian besar negara yang terkena dampak konflik Libya, angka di Nigeria menegaskan besarnya peningkatan dan pentingnya masalah ini, sehingga menyoroti perlunya pemahaman yang lebih mendalam mengenai konflik ini. elemen kunci konflik.
Menurut Olayinka Ajala, ada dua hubungan utama yang menonjol antara cara dan intensitas serangan dan non-pastoralisme. Pertama, jenis senjata dan amunisi yang digunakan para penggembala dan kedua, orang-orang yang terlibat dalam penyerangan. [5] Temuan utama dalam penelitiannya adalah bahwa senjata yang dibeli oleh para penggembala untuk melindungi ternak mereka juga digunakan untuk menyerang para petani ketika ada perselisihan mengenai rute penggembalaan atau perusakan lahan pertanian oleh para penggembala keliling. [5]
Menurut Olayinka Ajala, dalam banyak kasus, jenis senjata yang digunakan para penyerang memberikan kesan bahwa para penggembala migran mendapat dukungan dari luar. Negara Bagian Taraba di Nigeria Timur Laut adalah salah satu contohnya. Setelah serangan yang berkepanjangan yang dilakukan oleh para penggembala di negara bagian tersebut, pemerintah federal telah mengerahkan tentara di dekat komunitas yang terkena dampak untuk mencegah serangan lebih lanjut. Meskipun pasukan telah dikerahkan ke komunitas yang terkena dampak, beberapa serangan masih dilakukan dengan senjata mematikan, termasuk senapan mesin.
Ketua Pemerintah Daerah Daerah Takum, Negara Bagian Taraba, Bapak Shiban Tikari dalam sebuah wawancara dengan “Daily Post Nigeria” menyatakan, “Para penggembala yang sekarang datang ke komunitas kami dengan membawa senapan mesin bukanlah penggembala tradisional yang kami kenal dan hadapi saat ini. tahun berturut-turut; Saya menduga mereka mungkin telah dibebaskan sebagai anggota Boko Haram. [5]
Terdapat bukti yang sangat kuat bahwa sebagian dari komunitas penggembala bersenjata lengkap dan kini bertindak sebagai milisi. Misalnya, salah satu pemimpin komunitas penggembala membual dalam sebuah wawancara bahwa kelompoknya telah berhasil melakukan serangan terhadap beberapa komunitas petani di Nigeria utara. Ia menyatakan bahwa kelompoknya tidak lagi takut terhadap militer dan menyatakan: “Kami memiliki lebih dari 800 senapan [semi-otomatis], senapan mesin; Fulani sekarang punya bom dan seragam militer.” (Salkida, Ahmad, Eksklusif tentang penggembala Fulani: “Kami punya senapan mesin, bom dan seragam militer”, Jauro Buba; 07/09/2018). Pernyataan ini juga dibenarkan oleh banyak orang lain yang diwawancarai oleh Olayinka Ajala.
Jenis senjata dan amunisi yang digunakan dalam serangan para penggembala terhadap petani tidak tersedia bagi para penggembala tradisional dan hal ini menimbulkan kecurigaan pada para penggembala baru. Dalam sebuah wawancara dengan seorang perwira militer, ia menyatakan bahwa para penggembala miskin yang memiliki ternak kecil tidak mampu membeli senapan otomatis dan jenis senjata yang digunakan oleh para penyerang. Dia berkata: “Kalau dipikir-pikir, saya bertanya-tanya bagaimana seorang penggembala miskin mampu membeli senapan mesin atau granat tangan yang digunakan oleh para penyerang ini?
Setiap perusahaan mempunyai analisis biaya-manfaatnya masing-masing, dan para penggembala lokal tidak dapat berinvestasi pada senjata semacam itu untuk melindungi ternak kecil mereka. Agar seseorang mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk membeli senjata-senjata ini, mereka pasti telah berinvestasi besar-besaran pada ternak ini atau berniat mencuri ternak sebanyak mungkin untuk mendapatkan kembali investasi mereka. Hal ini semakin menunjukkan fakta bahwa sindikat atau kartel kejahatan terorganisir kini terlibat dalam migrasi ternak”. [5]
Responden lain menyatakan bahwa penggembala tradisional tidak mampu membayar harga AK47 yang dijual seharga US$1,200 – US$1,500 di pasar gelap di Nigeria. Selain itu, pada tahun 2017, Anggota Parlemen yang mewakili Negara Bagian Delta (Wilayah Selatan-Selatan) di Dewan Majelis, Evans Ivuri, menyatakan bahwa sebuah helikopter tak dikenal secara rutin melakukan pengiriman ke beberapa penggembala di Hutan Belantara Owre-Abraka di negara bagian tersebut, tempat mereka tinggal bersama ternaknya. Menurut pembuat undang-undang, lebih dari 5,000 sapi dan sekitar 2,000 penggembala tinggal di hutan. Klaim-klaim ini semakin menunjukkan bahwa kepemilikan sapi-sapi ini sangat dipertanyakan.
Menurut Olayinka Ajala, kaitan kedua antara modus dan intensitas serangan dengan non-pastoralisme adalah identitas orang-orang yang terlibat dalam serangan tersebut. Ada beberapa argumen mengenai identitas para penggembala yang terlibat dalam penyerangan terhadap petani, dan sebagian besar penyerang adalah penggembala.
Di banyak wilayah di mana petani dan peternak hidup berdampingan selama beberapa dekade, para petani mengetahui peternak yang ternaknya merumput di sekitar lahan pertanian mereka, periode mereka membawa ternak, dan jumlah rata-rata ternak. Saat ini, terdapat keluhan bahwa jumlah ternak lebih besar, para penggembala tidak dikenal oleh petani dan dipersenjatai dengan senjata berbahaya. Perubahan-perubahan ini membuat pengelolaan konflik tradisional antara petani dan penggembala menjadi lebih sulit dan terkadang tidak mungkin dilakukan. [5]
Ketua Dewan Pemerintahan Daerah Ussa – Negara Bagian Taraba, Bapak Rimamsikwe Karma, menyatakan bahwa para penggembala yang melakukan serangkaian penyerangan terhadap petani bukanlah penggembala biasa yang dikenal masyarakat setempat, dengan mengatakan bahwa mereka adalah “orang asing”. Ketua Dewan menyatakan bahwa “para penggembala yang datang setelah tentara ke wilayah yang diatur oleh dewan kami tidak ramah terhadap rakyat kami, bagi kami mereka adalah orang yang tidak dikenal dan mereka membunuh orang”. [5]
Klaim ini telah dibenarkan oleh militer Nigeria, yang mengatakan bahwa para penggembala migran yang terlibat dalam kekerasan dan penyerangan terhadap petani adalah “yang disponsori” dan bukan para penggembala tradisional. (Fabiyi, Olusola, Olaleye Aluko dan John Charles, Benue: Penggembala pembunuh disponsori, kata militer, 27 April 2018, Punch).
Komisaris Polisi Negara Bagian Kano menjelaskan dalam sebuah wawancara bahwa banyak dari penggembala bersenjata yang ditangkap berasal dari negara-negara seperti Senegal, Mali dan Chad. [5] Hal ini merupakan bukti lebih lanjut bahwa semakin banyak penggembala bayaran yang menggantikan penggembala tradisional.
Penting untuk dicatat bahwa tidak semua konflik antara penggembala dan petani di wilayah ini disebabkan oleh neo-pastoralisme. Peristiwa baru-baru ini menunjukkan bahwa banyak penggembala tradisional yang bermigrasi sudah membawa senjata. Selain itu, beberapa serangan terhadap petani merupakan pembalasan dan pembalasan atas pembunuhan hewan ternak yang dilakukan oleh petani. Meskipun banyak media arus utama di Nigeria mengklaim bahwa para penggembala adalah agresor dalam sebagian besar konflik, wawancara mendalam mengungkapkan bahwa beberapa serangan terhadap petani menetap merupakan pembalasan atas pembunuhan ternak para penggembala oleh para petani.
Misalnya, kelompok etnis Berom di Negara Bagian Plateau (salah satu kelompok etnis terbesar di kawasan ini) tidak pernah menyembunyikan kebencian mereka terhadap para penggembala dan kadang-kadang terpaksa menyembelih ternak mereka untuk mencegah penggembalaan di tanah mereka. Hal ini memicu pembalasan dan kekerasan yang dilakukan oleh para penggembala, yang mengakibatkan terbunuhnya ratusan orang dari komunitas etnis Berom. (Idowu, Aluko Opeyemi, Urban Violance Dimension in Nigeria: Farmers and Herders Onslaught, AGATHOS, Vol. 8, Issue 1 (14), 2017, p. 187-206); (Akov, Emmanuel Terkimbi, Perdebatan konflik sumber daya ditinjau kembali: Mengurai kasus bentrokan petani-penggembala di wilayah Tengah Utara Nigeria, Vol. 26, 2017, Edisi 3, African Security Review, hal. 288 – 307).
Menanggapi meningkatnya serangan terhadap petani, beberapa komunitas petani telah membentuk patroli untuk mencegah serangan terhadap komunitas mereka atau melancarkan serangan balik terhadap komunitas penggembala, yang selanjutnya meningkatkan permusuhan antar kelompok.
Pada akhirnya, meskipun elit penguasa pada umumnya memahami dinamika konflik ini, politisi sering kali memainkan peran penting dalam merefleksikan atau mengaburkan konflik ini, solusi potensial, dan respons negara Nigeria. Meskipun solusi potensial seperti perluasan padang rumput telah dibahas panjang lebar; melucuti senjata para penggembala bersenjata; manfaat bagi petani; sekuritisasi komunitas petani; mengatasi masalah perubahan iklim; dan memerangi gemerisik ternak, konflik tersebut dipenuhi dengan perhitungan politik, yang tentu saja membuat penyelesaiannya menjadi sangat sulit.
Mengenai akun politik, ada beberapa pertanyaan. Pertama, menghubungkan konflik ini dengan etnis dan agama sering kali mengalihkan perhatian dari permasalahan mendasar dan menciptakan perpecahan di antara komunitas-komunitas yang sebelumnya terintegrasi. Meskipun hampir semua penggembala berasal dari Fulani, sebagian besar serangan ditujukan terhadap kelompok etnis lain. Alih-alih mengatasi isu-isu yang diidentifikasi sebagai penyebab konflik, para politisi sering kali menekankan motivasi etnis untuk meningkatkan popularitas mereka dan menciptakan “patronase” seperti dalam konflik-konflik lain di Nigeria. (Berman, Bruce J., Ethnicity, Patronage and the African State: The Politics of Uncivil Nationalism, Vol. 97, Issue 388, African Affairs, Juli 1998, hlm. 305 – 341); (Arriola, Leonardo R., Patronase dan Stabilitas Politik di Afrika, Vol. 42, Edisi 10, Studi Politik Komparatif, Oktober 2009).
Selain itu, para pemimpin agama, etnis, dan politik yang berkuasa sering kali terlibat dalam manipulasi politik dan etnis ketika berupaya keras mengatasi masalah ini, yang sering kali hanya memicu ketegangan, bukan meredakan ketegangan. (Princewill, Tabia, Politik penderitaan orang miskin: Penggembala, petani dan manipulasi elit, 17 Januari 2018, Vanguard).
Kedua, perdebatan tentang penggembalaan dan peternakan seringkali dipolitisasi dan digambarkan dengan cara yang cenderung meminggirkan suku Fulani atau perlakuan istimewa terhadap suku Fulani, tergantung pada siapa yang terlibat dalam perdebatan tersebut. Pada bulan Juni 2018, setelah beberapa negara bagian yang terkena dampak konflik memutuskan secara individual untuk menerapkan undang-undang anti-penggembalaan di wilayah mereka, Pemerintah Federal Nigeria, dalam upaya untuk mengakhiri konflik dan menawarkan solusi yang memadai, mengumumkan rencana untuk mengeluarkan dana sebesar 179 miliar naira ( sekitar 600 juta dolar AS) untuk pembangunan peternakan jenis “peternakan” di sepuluh negara bagian. (Obogo, Chinelo, Geger atas usulan peternakan sapi di 10 negara bagian. Kelompok Igbo, Sabuk Tengah, Yoruba menolak rencana FG, 21 Juni 2018, The Sun).
Sementara beberapa kelompok di luar komunitas penggembala berpendapat bahwa penggembalaan adalah urusan pribadi dan tidak boleh mengeluarkan biaya publik, komunitas penggembala yang bermigrasi juga menolak gagasan tersebut dengan alasan bahwa hal tersebut dirancang untuk menindas komunitas Fulani, sehingga mempengaruhi kebebasan bergerak suku Fulani. Beberapa anggota komunitas peternakan menyatakan bahwa usulan undang-undang peternakan “digunakan oleh sebagian orang sebagai kampanye untuk memenangkan suara pada pemilu 2019”. [5]
Politisasi masalah ini, ditambah dengan pendekatan pemerintah yang santai, membuat setiap langkah penyelesaian konflik menjadi tidak menarik bagi pihak-pihak yang terlibat.
Ketiga, keengganan pemerintah Nigeria untuk melarang kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap komunitas petani sebagai pembalasan atas pembunuhan hewan ternak terkait dengan ketakutan akan rusaknya hubungan patron-klien. Meskipun Asosiasi Peternak Sapi Miyetti Allah Nigeria (MACBAN) membenarkan pembunuhan puluhan orang di Negara Bagian Plateau pada tahun 2018 sebagai balas dendam atas pembunuhan 300 sapi oleh komunitas peternak, pemerintah menolak untuk mengambil tindakan apa pun terhadap kelompok yang mengklaim bahwa hal tersebut adalah tindakan balas dendam. kelompok sosial budaya yang mewakili kepentingan Fulani. (Umoru, Henry, Marie-Therese Nanlong, Johnbosco Agbakwuru, Joseph Erunke dan Dirisu Yakubu, pembantaian Plateau, pembalasan atas hilangnya 300 ekor sapi – Miyetti Allah, 26 Juni 2018, Vanguard). Hal ini menyebabkan banyak orang Nigeria berpikir bahwa kelompok tersebut adalah kelompok yang sengaja diambil di bawah perlindungan pemerintah karena presiden yang menjabat saat itu (Presiden Buhari) berasal dari suku Fulani.
Selain itu, ketidakmampuan elit penguasa Nigeria dalam menghadapi dampak konflik berdimensi neo-pastoral menimbulkan masalah serius. Alih-alih mengatasi alasan mengapa pastoralisme menjadi semakin termiliterisasi, pemerintah malah berfokus pada dimensi etnis dan agama dalam konflik tersebut. Selain itu, banyak pemilik ternak dalam jumlah besar merupakan anggota elit berpengaruh yang memiliki pengaruh besar, sehingga sulit untuk menuntut tindakan kriminal. Jika dimensi neo-pastoral dari konflik ini tidak dikaji dengan tepat dan pendekatan yang memadai terhadap konflik tersebut tidak diterapkan, kemungkinan besar tidak akan ada perubahan dalam situasi di negara ini dan kita bahkan akan menyaksikan situasi yang semakin memburuk.
Sumber yang digunakan:
Daftar lengkap literatur yang digunakan pada analisis bagian pertama dan kedua diberikan pada akhir analisis bagian pertama, yang diterbitkan dengan judul “Sahel – konflik, kudeta, dan bom migrasi”. Hanya sumber-sumber yang dikutip pada bagian ketiga analisis ini – “Fulani, Neopastoralisme dan Jihadisme di Nigeria” yang diberikan di bawah ini.
Sumber tambahan diberikan dalam teks.
[5] Ajala, Olayinka, Pendorong baru konflik di Nigeria: analisis bentrokan antara petani dan penggembala, Third World Quarterly, Volume 41, 2020, Edisi 12, (diterbitkan online 09 September 2020), hlm.2048-2066,
[8] Brottem, Leif dan Andrew McDonnell, Pastoralisme dan Konflik di Sudano-Sahel: Tinjauan Literatur, 2020, Search for Common Ground,
[38] Sangare, Boukary, orang Fulani dan Jihadisme di Sahel dan negara-negara Afrika Barat, 8 Februari 2019, Observatoire Dunia Arab-Muslim dan Sahel, The Fondation pour la recherche stratégique (FRS).
Foto oleh Tope A. Asokere: https://www.pexels.com/photo/low-angle-view-of-protesters-with-a-banner-5632785/
Catatan tentang penulis:
Teodor Detchev telah menjadi profesor madya penuh waktu di Sekolah Tinggi Keamanan dan Ekonomi (VUSI) – Plovdiv (Bulgaria) sejak 2016.
Dia mengajar di New Bulgarian University – Sofia dan di VTU “St. St Cyril dan Methodius”. Saat ini ia mengajar di VUSI dan UNSS. Kursus pengajaran utamanya adalah: Hubungan industrial dan keamanan, Hubungan industrial Eropa, Sosiologi ekonomi (dalam bahasa Inggris dan Bulgaria), Etnososiologi, Konflik etno-politik dan nasional, Terorisme dan pembunuhan politik – masalah politik dan sosiologis, Perkembangan organisasi yang efektif.
Dia adalah penulis lebih dari 35 karya ilmiah tentang ketahanan api pada struktur bangunan dan ketahanan cangkang baja silinder. Ia adalah penulis lebih dari 40 karya mengenai sosiologi, ilmu politik dan hubungan industrial, termasuk monografi: Hubungan industrial dan keamanan – bagian 1. Konsesi sosial dalam perundingan bersama (2015); Interaksi Kelembagaan dan Hubungan Industrial (2012); Dialog Sosial di Sektor Keamanan Swasta (2006); “Bentuk Pekerjaan Fleksibel” dan Hubungan (Pasca) Industrial di Eropa Tengah dan Timur (2006).
Dia ikut menulis buku: Inovasi dalam perundingan bersama. Aspek Eropa dan Bulgaria; Pengusaha dan perempuan Bulgaria di tempat kerja; Dialog Sosial dan Pekerjaan Perempuan di Bidang Pemanfaatan Biomassa di Bulgaria. Baru-baru ini ia membahas isu-isu hubungan antara hubungan industrial dan keamanan; perkembangan disorganisasi teroris global; permasalahan etnososiologis, konflik etnik dan etno-agama.
Anggota Asosiasi Perburuhan dan Hubungan Ketenagakerjaan Internasional (ILERA), Asosiasi Sosiologi Amerika (ASA) dan Asosiasi Ilmu Politik Bulgaria (BAPN).
Demokrat Sosial dengan keyakinan politik. Pada periode 1998 – 2001, beliau menjabat sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja dan Kebijakan Sosial. Pemimpin Redaksi surat kabar “Svoboden Narod” pada tahun 1993 hingga 1997. Direktur surat kabar “Svoboden Narod” pada tahun 2012 – 2013. Wakil Ketua dan Ketua SSI pada periode 2003 – 2011. Direktur “Kebijakan Industri” di AIKB sejak tahun 2014 hingga saat ini. Anggota NSTS dari tahun 2003 hingga 2012.